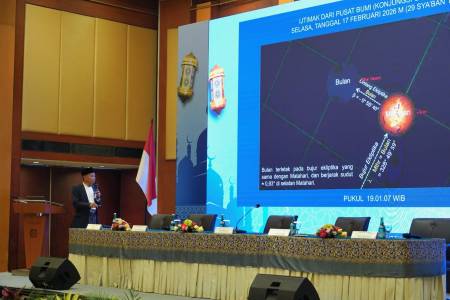Sebuah perspektif Imam Shamsi Ali
KABARINDO, NewYork- Pastinya suasana Ramadan itu masih terasa pada setiap detak nadi kehidupan kita.
Sesuatu yang telah menjadi narasi kehidupan dalam masa tiga puluh hari. Tentu Ramadan harusnya telah menjadi bagian dari ‘ma’ruf’ kehidupan yang mengalir pada setiap titik kehidupan kita.
Tidak lupa sekali lagi saya sampaikan tahniah, mubarak, selamat, atau juga dalam bahasa kampung saya; congratulations. Bahwa dengan izin dan qudrahNya juga kita telah menyelesaikan pelatihan yang dahsyat itu. Pelatihan “imsak” dalam kehidupan yang harusnya dirayakan dengan rasa bahagia, senang dan penuh kemenangan.
Kali ini saya ingin kembali mengingatkan diri saya dan kita semua tentang “keberkahan” Ramadan. Sebenarnya ini lanjutan dari reminder (pengingat) yang pernah saya sampaikan dalam beberapa tulisan selama Ramadan; memaknai keberkahan Ramadan. Walau judul berbeda tapi secara substansi sama.
Seperti yang pernah disampaikan bahwa puasa Ramadan memiliki keberkahan yang mencakup segala titik nadi kehidupan manusia. Dan karenanya sangat disayangkan jika keberkahan itu dibatasi pada keberkahan (kemanfaatan) ta’abbudiyah (ritual) semata.
Satu keberkahan yang ingin saya garis bawahi kali ini adalah bahwa Ramadan adalah bulan restorasi kehidupan. Maknanya bahwa di bulan Ramadan insan-insan Mukmin diberikan peluang emas untuk melakukan “ishlahaat” (perbaikan-perbaikan) mendasar dalam hidupnya.
Restorasi kehidupan menjadi bagian esensial dalam ajaran Islam. Bahkan sejatinya konsep taubat itu esensinya adalah restorasi. Restorasi kehidupan yang membawa kepada restorasi relasi, baik secara vertikal (dengan Pencipta) maupun secara horizontal (dengan sesama makhluk).
Di antara hal-hal mendasar yang memerlukan restorasi, khususnya dengan puasa Ramadan adalah restorasi “kemanusiaan” manusia.
Restorasi kemanusiaan menjadi sangat esensi karena selain menjadi identitas dasar kehidupan manusia, juga menjadi fondasi dalam menjalani misi kehidupan itu sendiri. Tanpa kemanusiaannya manusia menjadi makhluk yang nampak manusia tapi secara esensi telah kehilangan identitasnya sebagai manusia.
Kemanusiaan yang biasa disebut “insaniyat” atau lebih populer dalam bahasa agama dengan fitrah merupakan identitas dasar manusia. Artinya manusia jadi manusia karena kefitrahannya. Hal itu karena memang manusia diciptakan di atas kefitrahan itu.
“Dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia. (Dan fitrah itu) tiada tergantikan dalam penciptaan” (Ar-Rum).
“Semua manusia terlahir di atas fitrah. Orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi” (hadits).
Kemanusiaan itulah sesungguhnya yang menentukan wajah prilaku manusia. Ketika kemanusiaan berfungsi secara baik, akan terlahir apa yang disebut dengan “furqan” (pembeda) dalam hidupnya. Dengan furqan ini manusia akan mampu memilah dan memilih mana yang baik (benar) dari hal yang buruk (salah) dalam kehidupan.
Inilah pula makna utama dari diturunkannya Al-Quran. Bukan untuk membawa sesuatu yang asing/baru bagi kehidupan manusia. Tapi lebih kepada memainkan peranan “dzikra” (mengingatkan) sekaligus mengkonfirmasi akan kefitrahan manusia itu. Sehingga Al-Quran selain dikenal dengan “dzikra” (inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizhun), juga dikenal sebagai “Al-Furqan” (Al-Baqarah: 185).
Pada sisi lain kita sadari bahwa kerusakan yang terjadi di alam ini disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia yang fitrahnya telah terkontaminasi oleh berbagai najis kehidupan akibat dorongan hawa nafsu yang tiada terkendali.
“Kerusakan telah nampak di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia” (Ar-Rum).
Di sìnilah puasa yang beresensikan al-imsak (menahan diri) melatih manusia untuk melakukan reparasi atau restorasi kefitrahan tadi. Fitrah yang biasa diterjemahkan dengan “puritas” atau kesucian itu terjadi dengan melatih diri untuk menahan segala hal yang dapat menjadikan seseorang terjatuh ke dalam jebakan nafsu yang tak terkontrol.
Dengan menahan atau mengontrol (bukan mematikan) dorongan hawa nafsu, manusia akan mampu menata hidupnya sesuai dengan rasa kemanusiaannya. Rasa kehidupan yang terpoles keindahan (beauty), cinta (love), kasih sayang (compassion) dan tentunya dengan nilai (value) dan manfaat (benefit).
Inilah restorasi yang akan terjadi dengan puasa Ramadan. Puasa yang esensinya menahan hawa nafsu (ammarah) menumbuhkan batin yang furqan (membedakan mana baik dan buruk). Sehingga hidup semakin bertanggung jawab, bermakna dan bermanfaat…
Hal yang paling essensi dari hasil restorasi fitrah selama Ramadan adalah akan terjadi restorasi relasi dengan sang Khaliq. Sesungguhnya esensi dasar dari fitrah manusia itu adalah terbentuknya “covenant” (mi’tsaq) atau perjanjian kuat antara seorang manusia dan sang Khaliq.
Dalam ajaran Islam janji seorang hamba kepada Tuhannya ini ditegaskan dalam Al-Qur’an:
"Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka: bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Betul, kami bersaksi. (kami berjanji) agar di hari Kiamat kami tidak mengatakan, Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini," (Al-A'raf 7: Ayat 172)
Janji ini sekaligus seperti disebutkan terdahulu merupakan identitas dasar manusia yang disebut fitrah (insaniat). Dengannya manusia menjaga eksistensinya sebagai manusia. Dan tanpa dengannya manusia kehilangan identitas kemanusiaannya.
Sebagai bagian dari upaya menguatkan atau menyuburkan kembali kefitrahan itu selama Ramadan “convent” atau janji penghambaan (ubudiyah) kepada Allah dikuatkan. Sehingga Ramadan sangat dikenal sebagai bulan ibadah atau ubudiyah (syahrul ibaadaat).
Komitmen ubudiyah inilah yang menjadi bagian kedua dari restorasi yang terjadi selama Ramadan. Seorang hamba akan melakukan yang terbaik untuk merestorasi relasi dan komitmen ibudiyahnya kepada Allah SWT.
Barangkali ini pula salah satu rahasia kenapa ibadah-ibadah selama Ramadan diberikan nilai tambah yang berlipat. Amalan-amalan sunnah dimaknai atau dinilai seolah amalan fardhu. Berumrah di bulan Ramadan misalnya secara value (nilai) bagaikan menunaikan ibadah haji. Karena memang semua itu dimaksudkan utnuk mereparasi kembali relasi antara seorang hamba dan Tuhannya.
Puasa juga bahkan diakui sebagai amalan yang secara ekslusif menjadi milik Allah. Dalam hadits Qudsi disebutkan bahwa “semua amalan anak Adam adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah milikKu”.
Diakuinya puasa sebagai milik Allah ini tentu juga memberikan nilai Istimewa yang lain. Salah satunya karena puasa seolah mengembalikan manusia kepada identitas dasar dan misi utama hidupnya sebagai “abdullah”. Bahwa wujud manusia itu dan misi utamanya dalam hidup ini adalah “li’ibadatill” (penyembahan kepada Allah).
Permasalahannya memang manusia kerap kali menjadi lengah atau lupa. Kata manusia itu sendiri memiliki konotasi “nas-yun” (lupa). Yang Kemudian diperkuat oleh dorongan hawa nafsu di satu sisi dan tarikan dunia yang melupakan di sisi lain. Maka terjadilah “nasullaha fa ansaahum anfusahum” (mereka lupa kepada Allah maka mereka dijadikan lupa diri).
Di saat manusia lupa diri itulah terjadi prilaku yang tida alami. Banyak yang tidak sadar bahwa mengingkari Tuhan itu tidak alami. Tidak melakukan ubudiyah itu tidak alami. Hingga melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan keridhoaan Allah itu sesungguhnya tidak alami dalam hidup seorang manusia (yang Fitri).
Maka bulan Ramadan menjadi sarana yang sangat efektif untuk membangun kembali kesadaran ubudiyah itu. Di bulan inilah terjadi koneksi yang sangat intim dengan Pencipta.
Relasi ubudiyah yang begitu dekat itu digambarkan dalam sebuah ayat yang terletak di antara ayat-ayat puasa: “dan jika hamba-hambaKu bertanya padamu tentang Aku sampaikan bahwa Aku sangat dekat” (Al-Baqarah).
Restorasi kedekatan (Al-Qurbah) bahkan kebersamaan dengan Allah (ma’uyatullah) inilah yang menjadi esensi Ramadan. Dan dengan merestorasi kedekatan ini hidup manusia akan lebih bermakna dan fitri. Insya Allah!
New York, 3 Mei 2022
Penulis adalah Presiden Nusantara Foundation juga diaspora asal bumi Sawerigading.